Bagaimana idealnya hubungan cendekiawan vis a vis kekuasaan? Ada yang berpendapat, cendekiawan seharusnya tidak terlibat dalam kekuasaan. Yang lain melihat cendekiawan bisa berperan ganda; sebagai birokrat yang baik sembari tetap berperan sebagai intelektual yang jernih dan kritis. Namun, karena cendekiawan (intellectual) pada dasarnya lebih merupakan kapasitas dan kualitas ketimbang status dan posisi, cendekiawan dan kekuasaan sesungguhnya tidak perlu diposisikan kelewat dikotomis. Mengikuti Antony D. Smith (1981:109) yang melekatkan istilah intellectual untuk a type of personality and mental attitude, dapat dikatakan, kecendekiaan adalah kapasitas pribadi yang bisa dimiliki siapa pun sekaligus akumulasi peran seseorang di bidang-bidang non-intelektual, termasuk birokrasi.
Dengan alur argumen demikian, seorang cendekiawan takperlu dianggap kehilangan kecendekiaan hanya karena dia memegang kekuasaan formal dalam masyarakat. Banyak tokoh dalam pentas politik nasional yang bisa dijadikan contoh di mana peran cendekiawan dan negarawan terpadu secara harmonis. Sebutlah misalnya Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Soejatmoko, Mukti Ali, Emil Salim, Munawir Sjadzali, Quraish Shihab, dll. Tulisan ini berupaya menunjukkan beberapa contoh peran cendekiawan dalam kekuasaan politik di Sulawesi Selatan di masa lampau sebagaimana terlihat dalam konsep “topanrita.”
Secara etimologis, to panrita berarti orang yang menyaksikan. Kata panrita bisa berarti keahlian teknis, seperti tercermin dari ungkapan panrita lopi (ahli pembuat perahu). Walau setahu saya belum ada penelitian semantik atas konsep ini, saya menduga kata topanrita memiliki nisbah epistemologis dengan --jika bukan elaborasi dari-- kata Sanskerta ‘pandita,’ yang agaknya juga melahirkan kata ‘pendeta.’ Faktanya, dalam satu dan lain hal, sosok seorang pandita memang identik dengan peran sosok topanrita dalam masyarakat Bugis-Makassar. Menurut Mochtar Pabottingi, seorang cendekiawan asal Sulsel, topanrita adalah orang yang bersaksi, melihat dan menyimak atas suatu keadaan dan menyatakan keadaan sebenarnya. Di sini, topanrita bukan saja berperan sebagai pengamat yang objektif atas keadaan di sekitarnya, tapi juga memberi penilaian, kritik dan pertimbangan atas suatu keadaan. Dengan makna ini, tidak berlebihan jika topanrita diidentikkan dengan konsep cendekiawan (intellectual) dalam terminologi modern.
Kualitas dan kapasitas utama topanrita bisa disimpulkan dari paseng (petuah) Ma'danrengnge ri Majauleng yang bernama La Tenritau: "Aja' nasalaiko acca sibawa lempu" (Janganlah engkau kehilangan kecakapan dan kejujuran). Yang dimaksud La Tenritau dengan acca, kemampuan mengerjakan semua pekerjaan dan menjawab semua pertanyaan serta kecakapan berkata-kata baik, logis dan lembut sehingga menimbulkan kesan baik pada orang lain. Sementara lempu' adalah pola pikir dan prilaku yang selalu benar, tabiat baik dan ketakwaan kepada Dewata Seuwae (Tuhan Yang Esa).
Dalam perspektif masyarakat Bugis-Makassar, integrasi kecerdasan dan kejujuran merupakan kualifikasi penting setiap calon pemimpin. Ketika ditanya Arumpone (Raja Bone) tentang pangkal kecerdasan (appongenna accae), Kajao La Liddong –seorang cendekiawan dan mahapatih raja Bone-- menjawab: “lempue’” (kejujuran). Kajao La Liddong juga menyebut kejujuran raja (komalempu’i Arung Mangkaue) sebagai salah satu di antara tellu tanranna nasawe ase (syarat keberhasilan panen). La Waniaga Arung Bila, cendekiawan Soppeng abad ke-16, berkata: “Temmate lempu’e mawatang sapparenna atongengengnge’” (Kejujuran akan terus hidup, tapi kebenaran sulit dicari).
Di masa lalu masyarakat percaya, prilaku pemimpin menentukan kondisi kehidupan mereka. Hal ini turut berperan mengekang raja agar tidak bertindak sewenang-wenang demi terciptanya keadilan, keamanan dan kemakmuran dalam kerajaan. Menurut Andi Zainal Abidin, salah seorang di antara sangat sedikit ahli sejarah dan kebudayaan Sulsel, karena memiliki wewenang memperingatkan raja dan para pembantunya, negarawan dan ahli filsafat dahulu adalah faktor penting yang turut membatasi kekuasaan raja. Sekalipun A.Z. Abidin tidak secara eksplisit menyebut mereka topanrita, tapi peran mereka sepenuhnya identik dengan konotasi topanrita yang dikemukakan di atas. Maka, menurut Karaeng Pattingaloang, salah seorang ilmuan dan cendekiawan ulung kerajaan Gowa Tallo abad ke-17, salah satu di antara lima faktor keruntuhan suatu negeri (lima pammanjenganna matena butta lompowa) adalah jika tiada lagi cendekiawan di dalam negeri (punna tenamo tomangissengan ri lalang pa’rasanganga)(A.Z. Abidin, 1983:166-7).
Sebagai contoh, sebelum dilantik jadi datu Soppeng ke-9, Lamannussak To Akkarangeng mendatangi sejumlah topanrita di Sulsel, termasuk To Ciung Maccae (XV-XVI) di Luwu, guna mempelajari ilmu kepemimpinan. Salah satu paseng To Ciung kepada Lamannussak: “Jagaiwi balimmu wekka siseng, mujagaiwi rangeng-rangengmu wekka sisebbu, nasabak rangeng-rangeng mutu matuk solangiko” (Zainal Abidin, 1999:105) (Waspadailah lawan-lawanmu satu kali, waspadailah kawan-kawanmu seribu kali. Sebab yang terakhir inilah yang bisa membuatmu rusak). To Ciung juga menganjurkan Lammannussak sekali-sekali berkonsultasi dengan cendekiawan --yang tidak biasa berkunjung ke istana seperti halnya para oportunis—tentang masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan matang karena mereka mengatakan banyak kebenaran (Obbi’i to accae tassiseng-siseng mutanaiwi, nasaba’ maegatu patuju napau).
Di antara nama topanrita yang kerap muncul dalam wacana orang tua-tua Bugis-Makassar karena pesan-pesan mereka yang universal dan perenial --seperti direkam berbagai Lontara-- adalah To Ciung Maccae di Luwu (Abad XV), Nene Maggading di Suppa' (abad XV), La Tiringeng To Taba' di Wajo (Abad XV), La Waniaga Arung Bila di Soppeng (Abad XVI), Nene Pasiru' (Abad XV) dan La Pagala Nene Mallomo (Abad XVI) di Sidenreng, La Mellong Kajao La Liddong di Bone (abad XVI), Karaeng Botolempangan di Gowa (abad XVII), dan I Mangadacinna Daeng Sitaba Kareang Pattingalloang di Gowa-Tallo (abad XVII). Sosok La Tiringeng To Taba mungkin bisa diulas lebih jauh sekedar sebagai contoh.
Menurut Andi Pabarangi, peran La Tiringeng takdapat dipisahkan dari perjanjian awal antara rakyat dan raja Wajo di La Paddeppa’ yang berhasil merumuskan prinsip-prinsip utama ketatanegaraan (konstitusi) kerajaan Wajo. Abdurrazak Daeng Patunru dalam Sejarah Wajo (1964) menyatakan, lepas dari peran penting lima Arung Matowa Wajo terkemuka (La Tadampare', La Mungkace', La Tenrilai, La Salewangeng dan La Maddukelleng), La Tiringeng adalah tokoh besar Wajo. Arung Saotanre yang bergelar Arung Bettempola ini hidup sezaman dengan empat Arung Matowa Wajo yang pertama. Bettempola adalah negeri bagian kerajaan Wajo selain Talotenreng dan Tua.
Selama hidupnya, La Tiringeng kerapkali mengambil alih peranan Arung Matowa merumuskan berbagai undang-undang dan keputusan penting tentang berbagai masalah sosial-politik Wajo di abad ke-15 dan 16, masa-masa ketika kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya (Z.A. Farid, 1985). Karena kecerdasan dan kebijaksanaannya juga, La Tiringeng menjadi tempat orang-orang Wajo bertanya dan meminta nasehat atas beragam persoalan. Namun, dia selalu menolak permintaan (bahkan “tekanan”) rakyat Wajo agar dia menjadi Arung Matoa tiap kali terjadi kekosongan pemerintahan. Alasan dia, hal itu bertentangan dengan perjanjian awalnya dengan rakyat Wajo. Menurut A. Z. Abidin (1999), La Tiringeng dipandang pemimpin rakyat bukan saja karena ascribed status dan kesakralannya, tetapi juga terutama karena personal qualities dan jasanya menyusun dan melaksanakan sistem kekuasaan raja dan aparatnya yang terbatas. Tidak berlebihan jika A.D. Patunru (1964: 21) memandang La Tiringeng sebagai “ahli filsafat” Wajo.
Sebagaimana To Ciung Maccae, Nene Mallomo, Arung Bila, Kajao La Liddong dan Karaeng Pattingalloang, La Tiringeng mewujudkan diri sebagai sosok topanrita par excellence; seorang cendekiawan dan negarawan yang bijaksana dan cerdas, ahli hukum yang tegas, jujur dan tidak terbius kekuasaan dan kekayaan serta sangat mencintai rakyatnya. Tidak aneh, petuah-petuahnya ratusan tahun silam tampak masih relevan ditelaah sebagai sumber inspirasi dan pedoman dalam menata kehidupan sosial, hukum, politik dan pemerintahan di masa kini, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu pesan La Tiringeng, “Napoallebirengngi to Wajoe, maradekae, na malempu, na mapaccing ri gau’ salae, mareso mappalaong, na maparekki ri warang-paranna (ibid: 21). Maknanya, orang Wajo mulia karena mereka memiliki kebebasan, kejujuran, kesucian dari prilaku buruk, kerajinan bekerja, dan memelihara harta benda.
Setelah hampir seluruh kerajaan di Sulsel terislamisasi secara struktural pada awal abad ke-17, konsep topanrita tampaknya juga mengalami perkembangan. Kini topanrita lebih banyak merujuk kepada sosok ulama tradisional atau gurutta. Suatu hal yang tak mengherankan mengingat, setelah kedatangan Islam, muncullah ‘ulama yang mengambil alih peran topanrita dalam makna tradisionalnya. Ulama tradisional tidak saja menguasai ilmu-ilmu keislaman, tapi juga memahami masalah kejiwaan, kesehatan, sosial, hukum, budaya dan politik yang muncul dalam masyarakatnya. Wajarlah, mereka tidak saja menjadi gurutta (guru kita) dalam arti mengajari orang-orang tentang berbagai masalah agama, tetapi juga tempat meminta nasehat dan doa, misalnya, demi kesuksesan bisnis, keberhasilan panen, kesembuhan dari penyakit jasmani dan rohani, penyelesaian masalah hukum, kemenangan dalam pertempuran (ilmu kesaktian), dll.
Lebih penting lagi, para ulama juga berperan sebagai penasehat atau konsultan para raja (sultan) dalam menyelesaikan berbagai masalah kerajaan. Dalam terminologi modern, topanrita/ulama menjadi salah satu komponen penting civil society yang membatasi wewenang dan kekuasaan raja, sesuatu yang menjadi prasyarat demokrasi. Syekh Yusuf boleh jadi adalah contoh terbaik sosok ulama seperti ini di kerajaan Gowa dan Banten. Sementara AGH. Muhammad As’ad di Wajo dan AGH. Abdurrahman Ambo Dalle di Barru, sekedar menyebut dua contoh, adalah sosok topanrita di masa kontemporer.
Jadi, seperti ditunjukkan, dalam bidang sosial, hukum, budaya, agama dan kekuasaan politik, peran topanrita dalam masyarakat Sulsel sangat sentral. Hubungan harmonis dan saling menghargai antara para arung dan topanrita adalah salah satu faktor penting sehingga beberapa kerajaan tradisional Sulsel dapat mencapai puncak kegemilangan dalam fase-fase tertentu sejarah mereka. Prinsip sipakalebbi (saling menghormati), sipakatau (saling menghargai), dan sipakainge’ (saling mengingatkan) antara arung dan topanrita benar-benar terpelihara.
Walhasil, dalam konteks perpolitikan Sulsel kontemporer, apakah hubungan seperti ini masih terlihat di antara arung/penguasa dan topanrita/ulama? Masih banyakkah pejabat tinggi yang mau mendatangi cendekiawan/ulama dan meminta nasehat dan kritik dari mereka seperti dilakukan Lamannussak di atas? Atau, masihkah kita punya ulama dengan kualifikasi topanrita --dalam pengertian tradisionalnya-- yang senantiasa concern dengan masalah-masalah umat, termasuk berani menasehati dan mengoreksi pejabat? Semoga kedua pihak tidak malah suka sipakasiri’-siri’ (saling mempermalukan), sipakatau-tau (saling mengancam dan menakut-nakuti) dan sipakalinge’-linge’ (saling gila-gilaan) di mata rakyat? Saya optimis jawaban untuk ketiga pertanyaan di atas adalah positif.
** Sumber tulisan: http://wahyuddinhalim.blogspot.com

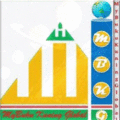


























No comments:
Post a Comment