Renungan Jum’at
:
Merajuk tradisi
Jawa ke dalam DDI
Oleh: Dr. M. Suaib Tahir
Sejak era Wali
Songo hingga saat ini, masyarakat Jawa telah mengenal Pesantren sebagai tempat
menimbah ilmu agama dan menjadikan sebagai pusat kegiatan ilmiah dan dakwah
masa itu. Dalam perkembangannya, Pesantren telah memproduksi putra-putra
terbaik bangsa sehingga tidak mengherankan jika dikatakan bahwa Pesantren dan
kiyainya telah memainkan peran penting dalam mencapai kemerdekaan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
Siapa diantara
kita khususnya kaum Nahdiyyin yang tidak mengenal KH. Hasyim Asy’ari sebagai
tokoh pendiri NU dan Pesantren Tebuireng di Jawa Timur dan sederatan ulama
lainnya yang telah memainkan peran dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa
termasuk Gurutta sebagai Pendiri DDI di Sul-Sel. Pesantren-Pesantren tersebut
di Jawa hingga saat ini masih eksis dan tetap memegang teguh sistem pendidikan
yang telah dikembangkan oleh sang pendiri.
Yang menarik
sekali karena di tengah-tengah era globalisasi dan maraknya madrasah-madrasah
yang menawarkan pendidikan agama dengan sistim moderen. Namun tetap menjadi
idola masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya guna menggali ilmu pengetahuan
dan menjadi tujuan para profesionalisme untuk berwisata ruhani di sela-sela
kekosongannya khususnya di bulan Ramadhan. Bahkan yang lebih menarik lagi
karena para tokoh di Pesantren tersebut menjadi inspirasi bagi setiap politikus
yang ingin berkuasa di negeri kita sehingga hampir setiap politikus tidak akan
berani maju ke ke dalam kancah pertarungan politik sebelum mendapatkan restu
dari sang-sang kiyai pemimpin di Pesantren tersebut.
Muncul
pertanyaan, apa yang mengakibatkan sehingga Pesantren di Jawa bisa tetap eksis,
berjaya dan berwibawa walaupun telah ditinggal mati sang kiyainya puluhan tahun
yang lalu bahkan berabad-abad. Namun, tetap menjadi idola msyarakat,
professional dan para politikus?. Apakah karena Pesantren tersebut memiliki
dana sehingga tidak membutuhkan sumbangan dari luar? Ataukah karena pemimpinnya
memiliki kharisma, tulus, ikhlas dan komitmen sehingga pesantren tersebut tetap
eksis?.
Di Jawa berlaku
sistim dinasti dalam kepemimpinan Pesantren. Sistim ini tidak termuat dalam
AD-ART. Akan tetapi sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa dirubah dan menjadi
konsensus masyarakat dan para ahli Pesantren. Bahkan di NU sendiri terkesan
berlaku sistim ini, sehingga jika Ketua Tanfiziyah bukan dari bani Hasyim
Asy’ari atau yang dipilih oleh mereka, maka kemungkinan Pengurus tersebut dalam
masa periodenya akan mengalami hambatan atau akan disingkirkan oleh kaum
sarungan yang merupakan penentu utama dalam tubuh NU yang mayoritasnya berasal
dari bani Hasyim dan cucu-cucunya.
Di Jawa, jika
seorang pimpinan Pesantren atau sang Kiyai meninggal dunia, maka kepemimpinan
otomatis akan beralih ke anak pertamanya yang laki-laki. Jika tidak terdapat
anak laki-laki, maka akan diserahkan kepada saudara atau keluarga terdekat.
Jika tidak terdapat keluarga dekat secara hubungan darah, maka akan diserahkan
ke menantu Sang Kiyai. Orang Jawa meyakini bahwa jika kepemimpinan dialihkan
kepada yang bukan keluarga sang kiyai, maka Pesantren dipastikan tidak akan
berjalan dan lambat laun akan mengalami kemundurun.
Hal ini karena
integritas yang bukan keluarga sang kiyai sangat minim dibanding integritas
keluarga sang kiyai walaupun orang lain itu pintar di banding putra sang kiyai.
Dengan menunjuk putra sang Kiyai, maka Pesantren akan hidup secara
berkesinambungan mengingat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi dan akan selalu
mendukung putra sang kiyai dalam menghadapi berbagai tantangan di sekitarnya.
Karena itu, pemimpin-pemimpin Pesantren di Jawa, sejak dini telah berusaha
semaksimal mungkin membentuk regenerasi dari keluarganya untuk melanjutkan
kepemimpinan Pesantren yang telah dibangun oleh sang ayah. Bahkan mereka tidak
tanggung-tanggung mengirim putranya ke luar negeri dengan harapan kelak akan
menjadi Passelle Pasau atau menjodohkan putrinya dengan seorang calon kiyai.
Kepemimpinan
seperti in memang agak aneh di tengah-tengah kehidupan demokrasi dan reformasi
khususnya di era globalisasi ini. Namun ini suatu fakta nyata yang harus diakui
dan diterima karena tradisi kepemimpinan seperti ini bukan saja berlaku di
Pesantren. Akan tetapi juga di perusahaan-perusahaan swasta, dulu dan sekarang.
Sebuah perusahaan bergensi tidak akan berlangsung lama sepeninggal pendirinya
jika yang memimpin perusahaan dimaksud berasal dari orang lain bukan saja di
Indonesia tetapi juga di Arab dan Eropa.
Sistim
kepimpinan Dinasti ternyata tetap dibutuhkan dalam ruang lingkup tersendiri
karena sistim ini bukan saja memiliki keistimewaan seperti integritas tinggi
sang penerus dalam melanjutkan perjuangan pendahulunya tetapi yang paling
penting adalah tanggung jawab sang penerus untuk memelihara dan mengembangkan
amanah dan warisan karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sang
pendahulunya.
Bagaimana
dengan DDI? Apakah setelah Gurutta meninggal diambil alih oleh putra pertamanya
atau keluarga dekat, atau orang lain? Apakah DDI masih seperti dulu atau
bagaimana? Bagaimana kepercayaan masyarakat setempat terhadap Pesantren DDI?
Masihkah seperti dulu atau bagimana?.
Sejumlah
pertanyaan yang perlu kita jawab secara seksama selaku warga DDI, lalu
memikirkan bagaimana selanjutnya dan apa yang harus dilakukan di masa yang akan
datang. Jika sebagian alumni memang melihat bahwa DDI sudah tidak lagi seperti
dulu ketika Gurutta masih ada, dan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah DDI
sudah tidak lagi seperti dulu dan masih ada harapan dan peluang untuk berkreasi
lebih banyak demi DDI, maka tidak ada salahnya, jika alumni-alumni DDI di
manapun berada berinisiatif untuk membentuk sebuah perhimpunan untuk melakukan
perubahan, perbaikan atau reformasi dalam tubuh DDI dengan merajuk sistim kepemimpinan
Pesantren di Jawa ke dalam tubuh DDI.
Sekian.

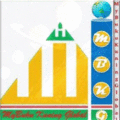





























No comments:
Post a Comment